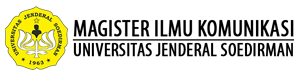King Anugrah Wiguna, S.Ikom., M.A.
King Anugrah Wiguna, S.Ikom., M.A.
Setelah kemeriahan ramadan dan lebaran dengan segala hal didalamnya, dunia digital kita khususnya sosial media diisi dengan kemeriahaan baru. Apalagi jika bukan euforia timnas sepakbola dengan kemenangan-kemenangannya. Publik digital Indonesia atau yang kita kenal dengan netizen, ramai membicarakan progress kemampuan timnas, membagikan cuplikan gol, memberikan selamat hingga membuat berbagai konten tentang timnas. Ditengah-tengah ramainya pemberitaan timnas di ruang digital kita, Gunung Ruang di Sulawesi Utara meletus dan ribuan orang diungsikan karenanya. Tentu ini bukan kejadian bencana alam biasa, bayangkan, ribuan orang harus dievakuasi!
Sayangnya pemberitaan Gunung Ruang tidak sesanter pemberitaan timnas, tidak banyak yang membicarakannya di sosial media. Bahkan mungkin saja tidak banyak netizen yang tahu tentang kejadian ini. Fenomena serupa terjadi belum lama ini ketika banjir melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah. 90 desa di 11 kecamatan di Demak terendam banjir selama lebih dari lima hari dan 24.436 orang diungsikan, menjadikan banjir kali ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir (BBC.com, 2024). Sayangnya, kejadian itu agaknya kalah populer dengan momen hiruk pikuk pemilu. Sosial media dan ruang-ruang digital saat itu dipenuhi dengan pembicaraan netizen tentang serba serbi pemilu, meme capres dan cuplikan-cuplikan video lucu debat capres.
Dua contoh kejadian di atas mungkin tidak sepenuhnya salah netizen. Algoritma sosial media yang semakin canggih dalam menghadirkan konten-konten yang kita sukai harus diakui juga memiliki peran atas fenomena diatas. Kita semakin dimanjakan dengan konten-konten yang hanya kita sukai yang muncul pada linimasa sosial media kita, membuat kita seakan memiliki gelembung informasi. Hal tersebut yang kemudian memiliki potensi bahaya bagi kita semua. Fenomena gelembung informasi ini dalam literasi digital dikenal dengan istilah ‘Echo Chamber’.
Secara sederhana, echo chamber merupakan kondisi di mana seseorang hanya menemukan informasi atau pendapat yang mencerminkan dan memperkuat pendapat mereka sendiri. Fenomena echo chamber terjadi disebabkan oleh adanya filter bubble, kondisi tersebut akan membuat pengguna media sosial terisolir dari berbagai informasi dan hanya meyakini kebenaran yang selama ini didapatkannya dari terpaan konten-konten sejenis (GCFLearn, 2019). Selain itu echo chamber juga dapat menciptakan misinformasi dan memutarbalikkan sudut pandang seseorang sehingga mereka kesulitan mempertimbangkan sudut pandang yang berlawanan dan mendiskusikan topik yang rumit. Hal ini sebagian dipicu oleh bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk menyukai informasi yang memperkuat keyakinan yang ada.
Fenomena-fenomena ini rasanya tidak asing bagi kita, tentu sekarang kita jamak menjumpai bagaimana penggunaan buzzer dan akun anonim yang melakukan penggiringan opini dengan melakukan misinformasi, disinformasi dan malinformasi untuk menutupi fakta maupun untuk pembentukan image tertentu.
Pada level global, fenomena echo chamber ini menjadi perhatian serius pemerintah Amerika Serikat ketika mereka memutuskan memblokir platform Tiktok. Alasannya, Tiktok dianggap memiliki potensi pembentukan echo chamber melalui algoritma yang mereka miliki. Marco Rubio, wakil ketua Komite Khusus Intelijen Senat dari Partai Republik, mengungkapkan “Mereka kebetulan mengendalikan perusahaan yang memiliki salah satu algoritma kecerdasan buatan terbaik di dunia. Algoritma inilah yang digunakan di negara ini oleh TikTok, dan menggunakan data orang Amerika untuk membaca pikiran Anda dan memprediksi video apa yang ingin Anda lihat” (CNN, 2024).
Bagaimana dengan Indonesia? sejauh ini pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi tentang moderasi platform sosial media. Hal ini berarti platform sosial media di Indonesia tidak memiliki kewajiban apa-apa terkait sistem algoritma dan konten-konten yang ada di platform mereka. Tentu saja ini membuat kita sebagai pengguna sosial media menjadi penanggung jawab bagi diri kita sendiri. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk membekali diri dalam menghadapi echo chamber di ruang digital ini? jawabannya adalah kemampuan literasi digital yang baik.
Literasi digital, tidak hanya berbicara mengenai kecakapan penggunaan perangkat digital atau bisa tidaknya seseorang memanfaatkan aplikasi-aplikasi digitalnya. Lebih penting dari itu, literasi digital menekankan kemampuan berpikir kritis. Hal ini senada dengan pendapat Gilster (1997) yang mendefinisikan literasi digital sebagai “kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format” dengan penekanan pada kemampuan berpikir kritis dibandingkan dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi saja. Kemampuan kritis ini menjadi nilai utama dalam literasi digital. Hal ini karena dunia digital tidak hanya melahirkan perangkat-perangkat teknologi yang perlu untuk kita tau cara penggunaannya, namun juga melahirkan pandangan dan cara baru dalam kehidupan kita. Tidak berlebihan kemudian literasi digital didapuk sebagai salah satu modal abad 21 (UNESCO, 2018).
Kemampuan berpikir kritis dalam literasi digital tidak bisa diukur dari tingkat pendidikan, ekonomi dan umur. Ia erat kaitanya dengan pengetahuan yang perlu kita pahami, kemampuan yang perlu kita latih dan cara yang perlu kita biasakan. Anda bisa mencari cara-cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis, membaca literatur tentang kompetensi literasi digital atau bahkan mengikuti kelas-kelas pelatihan tentangnya. Banyak materi yang perlu anda pelajari untuk menguasai kemampuan tersebut. Namun, ada satu hal sederhana yang bisa membantu melatih kemampuan berpikir kritis kita yaitu kepekaan. Kepekaan merupakan modal awal dalam berpikir kritis. Dengan memiliki kepekaan, kita setidaknya bisa membatasi diri kita untuk tidak cepat bereaksi, lebih bijak serta berikir terkait etika dan empati ketika berada di ruang-ruang digital. Hal ini tentu saja modal penting yang jika dilakukan secara konsisten dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis seperti melakukan cross check, prebunking, debunking dan lain sebagainya.
Jika kepekaan digital ini bisa kita miliki secara kolektif sebagai netizen Indonesia, bukan tidak mungkin ruang digital kita bisa menjadi lebih aman dan sehat. Disisi lain kita juga bisa menghindari fenomena echo chamber dalam gempuran algoritma yang semakin canggih dan memanjakan kita. Dengan kepekaan digital ini kita tentu bisa lebih bijak dalam menyelami ruang digital, seperti tidak ber-euforia secara berlebihan dalam merayakan kemenangan timnas ketika kita tahu saudara-saudara kita harus pergi dari rumahnya karena mengungsi dari gunung meletus misalnya.