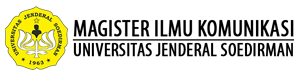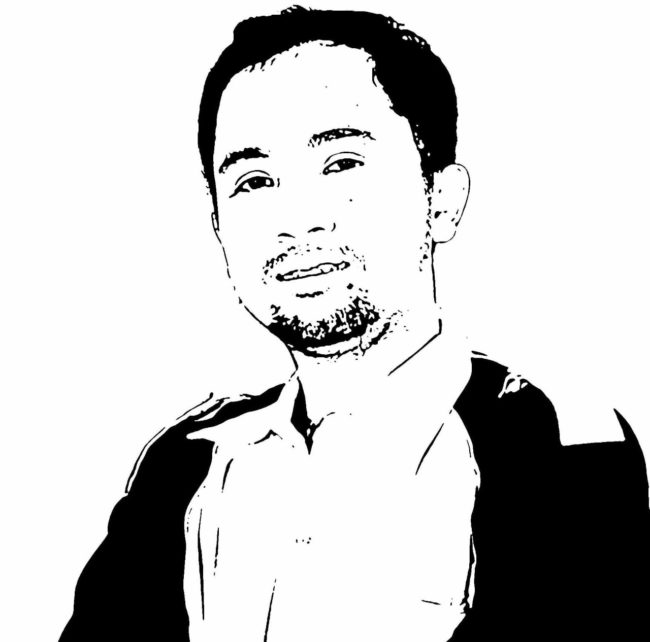Barangkali kita sering mendengar seloroh, “Orang komunikasi kok tidak komunikatif.” Maksudnya, orang belajar komunikasi—entah mahasiswa atau dosen jurusan komunikasi tapi tidak cakap dalam berkomunikasi. Memang, yang sering dianggap sebagai kecakapan komunikasi itu kemampuan bicara. Itulah yang paling mudah terlihat.
Kalau ukurannya kemampuan bicara, kita akan terkejut lagi dengan fakta: Pendiri kajian Ilmu Komunikasi di perguruan tinggi, Wilbur Schramm ternyata tak pandai bicara. Benar, karena dia memang gagap sejak kecil. Seperti diceritakan Everett M Rogers dalam bukunya ‘A History of Communication Study’, Schramm mengalami gagap bicara sejak umur 5 tahun, karena operasi amandel yang kurang baik. Pidatonya sangat memalukan bagi diri dan keluarganya.
Schramm selalu menghindari berbicara di depan publik. Sebagai ganti dari pidato perpisahan SMA nya, Schramm memainkan The Londonderry Air dengan flutenya. Namun, saat ia lulus cumlaude dari Marietta College pada jurusan sejarah dan ilmu politik pada tahun 1928, dia memberikan pidato perpisahan.
Tentu saja, komunikasi verbal tak semata soal bicara, karena juga ada komunikasi tertulis. Schramm memang tak pandai bicara, tetapi dia jago menulis. Dia membiayai kuliahnya di Universitas Harvard dengan bekerja paruh waktu sebagai reporter olahraga pada koran Marietta Register dan Boston Herald. Dia memenangkan juara tiga O.Henry Prize dalam dunia menulis fiksi pada tahun 1942.
Ungkapan ‘orang komunikasi tapi tidak komunikatif’ bisa juga menggambarkan realitas paradoksal yang terjadi dalam bidang disipilin lain. Orang Filsafat tapi tidak bijak. Orang Administarsi tapi tidak tertib aturan. Orang Hukum tapi hobi melanggar aturan. Orang Sosiologi tapi tak bisa bergaul dengan masyarakat. Dan yang lainnya.
Kalau kata orang Jawa, itu semacam ‘Jarkoni’: Iso ngajar tapi ora iso nglakoni. Bisa mengajarkan tetapi tidak bisa menjalankan. Sindiran semacam ini sebetulnya positif, menjadi tantangan bagi para akdemisi untuk perform dengan apa yang dipelajari. Tentu bukan dalam konteks membandingkan kapasitas teknis antara praktisi dengan akademisi. Anda pasti tahu hasilnya jika dilakukan ujia beda.
Pada beberapa ilmu—terutama yang berdimensi praktis, memang ada keunggulan akademisi yang berlatar belakang praktisi. Mereka punya keunggulan pengalaman di dunia kerja. Tapi tak semua ilmu menuntut kapasitas praktis, misalnya pada ilmu-ilmu dasar. Ilmu komunikasi yang praktis itu tetap saja dibangun dari fondasi ilmu-ilmu dasar seperti Filsafat, Sosiologi, Antropologi, atau Psikologi.
Aspek paling penting dari komitmen pada ilmu pengetahuan adalah dedikasi dan cinta. Itulah yag ditunjukkan Schramm. Rasa frustasi pada kemampuannya untuk berbicara melecutnya untuk meletakkan fondasi bidang kajian komunikasi di perguruan tinggi. Dengan tekun, dia kumpulkan pemikiran dan hasil penelitian berbagai ilmuwan di masa Perang Duna II (dengan berbagai latar belakang) yang masuk dalam domain komunikasi, seperti Kurt Lewin, Paul F. Lazarsfeld, Carl I. Hovland, dan Harold D. Laswell. Mereka inilah para founding fathers Ilmu Komunikasi
Sungguh tak terbayang, seorang anak yang gagap bicara kemudian mengajar dan menjadi profesor di Universitas Iowa. Schramm bahkan kemudian mengepalai workshop penulisan Iowa yang nantinya menjadi cikal bakal program doktor Ilmu Komunikasi di perguruan tinggi bergengsi tersebut.
Membayangkan komunikasi sebagai bidang kajian yang sangat luas, sungguh terbuka lebar kontribusi bagi sesama, baik dalam konteks komunikasi personal, kelembagaan, atau massa. Peran-peran akademisi komunikasi akan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Prasyaratnya, cinta dan komitmen kita pada pengembangan ilmu komunikasi. Agar tak lagi dibilang, ‘Orang komunikasi yang tak komunikatif’. Bagi akademisi komunikasi, ‘komunikatif’ bisa dibaca sebagai menjiwai Ilmu Komunikasi.