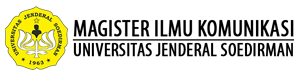Kang Jalal telah pergi. Tapi namanya akan tetap abadi. Setidaknya bagi para pembelajar komunikasi di negeri ini. Bahkan sosoknya secara pribadi mewakili idealitas praktik komunikasi: jago beretorika, handal dalam menulis. Dua kemampuan yang jarang berkumpul dalam diri seseorang. Seringnya, banyak yang jago pidato, tetapi tak bisa menulis. Atau, pandai berbahasa tulis, tetapi kesulitan berbahasa lisan.
Lebih dari itu tentu perannya dalam ikut membangun fondasi ilmu komunikasi—yang kehadirannya relatif baru di Indonesia tak dapat dipungkiri. Rasanya tak ada dosen atau mahasiswa yang tak kenal buku legendarisnya: Psikologi Komunikasi. Buku ini diterbitkan tahun 1985 oleh Rosdakarya. Sampai sekarang masih terus dicari.
Bayangkan berapa ratus ribu eksemplar yang berdar, baik yang asli ataupun bajakan. Bahkan di luar orang Komunikasi dan Psikologi terpikat dengan buku ini. Apa yang disajikan sangat mendalam, otentik, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Contoh-contohnya sangat membumi. “Gara-gara buku Psikologi Komunikasi ini, saya ambil S2 Psikologi Sosial,” cerita seorang dosen.
Ada juga buku Metode Penelitian Komunikasi yang pada masa awal terbit—kalau tidak salah di akhir tahun 1980 an, sangat dibutuhkan mereka yang ingin belajar riset kuantitatif dengan mudah. Terutama bagi mahasiswa seperti dengan otak pas-pasan seperti saya. Lewat penjelasan Kang Jalal, aplikasi statistik yang rumit terasa jadi asyik.
Dalam perjalanannya, Kang Jalal banyak mengkritik metode-metode kuantitaif yang dianggap terjebak dalam reduksi dan simplifikasi. Dia kemudian memilih untuk mengajarkan pendekatan kualitatif, terutama dalam analisis teks. “Buku-buku metodologi tak lagi terpajang di ruang tamunya,” cerita seorang koleganya dari Unpad.
Tentu momen membahagiakan bagi saya adalah ketika bisa belajar tatap muka dengan sosok yang seolah tak pernah lepas dari kontroversi ini. Terima kasih Dr Antar venus yang berhasil merayunya untuk mau mengajar di kelas teori komunikasi di program pascasarjana Komunikasi Unpad, tahun 2006. Meski hanya masuk kelas dua kali.
“Dua gelas susu itu lebih baik daripada lima ember comberan,” candanya waktu itu. Tentu bukan maksud Kang Jalal menegasikan dosen lain. Tapi itu seperti bentuk penghiburan, “Jangan kecewa, meski hanya dua kali ketemu, kalian akan dapat daging semua.” Memang sih, itu yang kami rasakan.
Selain ‘clarity’—yang menjadi ciri khasnya ketika menerangkan sesuatu, keunggulan Kang Jalal adalah menanamkan filosofi dari sebuah konsep, pendekatan, atau metode. Kata-katanya yang sering saya ulang di depan mahasiswa soal Analisis Wacana Kritis, “CDA–Critical Discourse Analyisis, lebih dari sekadar metode, tetapi ini adalah gerakan sosial. Karena ada semangat dismentling, membongkar praktik-praktik kekuasaan di balik teks.”
Sungguh menarik ketika Fikom Unsiba menginisiasi diskusi tentang pemikiran Kang Jalal sebagai komunikolog. Saya menantinya. Apalagi para pembahasnya adalah para pakar komunikasi, seperti Prof Deddy Mulyana sudah menyatakan akan ambil bagian. Sayang, acara ini mendadak dibatalkan. Padahal, menurut panitia, ratusan orang sudah mendaftar sebagai peserta diskusi.
“Ada tekanan dari internal dan eksternal kampus,” kata panitia. Penjelasan pendek yang maknanya gamblang. Seperti yang semiotika ajarkan, ketidakhadiran tanda dalam sebuah pesan adalah pesan tersendiri. Anda tahu, pelarangan ini tentu tak ada hubungannya dengan Ilmu Komunikasi—yang menjadikan Kang Jalal sebagai salah satu ikonnya di Indonesia.
Faktanya memang, di negeri +62 ini, kebebasan akademik seringkali menjadi ilusi. Hanya karena keyakinan seseorang, pemikirannya tentang sebuah ilmu pengetahuan menjadi terlarang untuk dibincangkan. Ternyata kita masih sulit membedakan antara keyakinan, pilihan politik, dan jalan pengetahuan seseorang.
Akhirnya, selamat jalan Kang Jalal. Mengutip kata-kata seorang kolega, apapun keyakinanmu, kontribusimu pada pengetahuan tak akan terlupakan.
–(Dr. Edi Santoso, Korprodi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman)