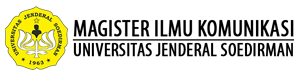Media sosial menjadi salah satu ruang untuk berinteraksi satu sama lain masa kini. Di dalamnya terkandung unsur-unsur seperti narsisme, anarkisme, juga kekerasan simbolik yang berpotensi merisikokan hubungan antarmanusia di dunia nyata. Literasi media dalam keluarga dan sekolah serta kontrol diri ketika berselancar di media sosial menjadi tantangan warganet Indonesia demi mewujudkan bangsa yang kian beradab.
Hal itu mengemuka dalam diskusi online bertema “Narsisme dan Anarkisme di Media Sosial: Perspektif Psikologi Komunikasi” yang digelar Progam Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kamis (1/4/2021).
Hadir sebagai pemantik diskusi adalah Dr. Ugung Dwi Ario W., M.Si, Psikologi dosen pada Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Dr. Wisnu Wijanarko, M.Si dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed, Wilibrordus Megandika W. S.S. sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Komunikasi Unsoed. Diskusi yang diantar oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Unsoed Dr. Edi Santoso, M.Si itu dimoderatori oleh Annisa Fasya Hapsari, S.I.Kom sebagai mahasiswi Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
Dr. Ugung memaparkan bahwa narsisme dan anarkisme merupakan dua hal yang berbeda dalam kajian, tapi menarik dibahas dalam media sosial. Narsisme itu sudah muncul dalam diri manusia sejak dulu sebelum ada era media sosial. Misalnya orang-orang ingin tampil di TV juga menjadi bentuk keinginan untuk menunjukkan diri. Kini di mana terdapat data sebanyak 160 juta orang Indonesia atau sekitar 59 persen dari total populasi yang aktif di media sosial, orang-orang bisa kian leluasa menunjukkan dirinya.
Menurut Dr. Ugung, jika melihat Pedoman Diagnosis Gangguan Jiwa seri 3 dan 5, sebetulnya narsisitik itu termasuk dalam gangguan jiwa ringan. “Istilah narsistik atau narsisme itu juga agak menyimpang: narsis dalam bentuk foto, diposting, untuk jadi status, itu sekarang dianggap sebagai narsis. Banyak istilah psikologi yang itu adalah gangguan jiwa ringan atau berat tapi digunakan secara umum,” katanya.
Dr. Ugung menyampaikan, dalam teori psikologi, manusia memiliki sejumlah kebutuhan termasuk di antaranya adalah need of exhibition. “Dari teori yang ada, narisistik itu naluri manusia meski di diagnostik adalah gangguan jiwa ringan,” ujarnya.
Merujuk pada suatu riset di Inggris terhadap respondens yang berusia 18-24 tahun, Dr. Ugung menyebutkan dalam sehari ada 1 juta foto diri atau swafoto yang dibuat baik berupa selfie maupun wefie. “Swafoto juga bukan melulu narsis, tapi juga itu menunjukkan eksistensi,” paparnya.
Sementara itu terkait anarkisme verbal dan nonverbal, Dr. Ugung menyampaikan, dalam media sosial hal itu bisa berwujud tulisan, film, atau gambar. Dalam fenomena terorisme yang terjadi di Makassar dan Mabes Polri, Dr Ugung menilai, pelaku tidak sekadar aktif di media sosial, tapi juga sudah didekati secara intensif oleh orang atau kelompok tertentu. “Jika mereka disebut pengantin yang dilempar jadi bomber, menyediakan diri untuk jadi tumbal untuk sebuah misi golongan tertentu, maka dia pasti sudah ada beliefe yang sudah diolah. Ini saya yakin tidak sekadar dia ada di medsos dan internet, tapi pasti ada unsur-unsur pembelajaran secara intensif dengan seseorang atau satu kaum,” tuturnya.
Menurut Dr. Ugung pendidikan bermedia sosial sejak dini perlu dilakukan mulai dari keluarga serta sekolah dasar. “Kita lemah dalam parenting. Bagaimana menggunakan internet dengan bijak dan sehat itu diajarkan terhadap anak-anak SD di Singapura. Harus ada pendidikan yang baik terhadap pengguna medsos mulai dari keluarga dan sekolah. Harus ada pembaruan kurikulim di era disrupsi kali ini. Terutama di sekolah dasar dan diikuti secara berjenjang,” paparnya.
Dr. Wisnu menyampaikan, jika dipakai secara berlebihan, media sosial menjadi panggung untuk menampilkan diri yang bukan apa adanya. Menurutnya, orang bisa berbeda dari kenyataan dan di media social karena di sana terdapat keintiman yang berjarak. Artinya di media sosial karena kita bisa sangat dekat, sangat terlibat dalam interaksi, dan ada ruang yang sangat aman, lalu kita menampilkan diri yang kita inginkan. kita menciptkan peran yang kita inginkan seperti kata Erving Goffman. “Jadi masalah kalau orang memaksakan diri di media sosial. Ketika satu kebohongan diciptakan maka ada kebohongan lain yang dilakukan untuk menutupi,” tuturnya.
Menurut Dr. Wisnu, dalam bermedia sosial, dibutuhkan pendidikan atau literasi media supaya orang-orang sadar dan terbiasa melakukan verifikasi informasi yang hadir di sana. Hal itu jadi tantangan pegiat pembelajar komunikasi bagaimana mengedukasi, membuat masyarakat literer ketika kita mengunggah, menampilkan sesuatu itu punya konsekuensi. “Tidak hanya pada aspek hukum, yang jelas ada UU ITE, legalnya, tapi dari konteks psikologi komunikasi, kalau kita menyampaikan atau memproduksi dan mereproduksi informasi yang punya potensi eskalatif, agresif, atau juga perundungan, menyerang kompetensi atau kepribadian karakter orang itu akan membuat interaksi kita jadi tidak baik,” paparnya.
Dr. Wisnu juga mengajak peserta diskusi untuk mengingatkan sesama teman-temannya jika mereka mengunggah sesuatu yang berpotensi berita bohong atau memicu konflik. “Jangan sampai karena rikuh, tidak enak, maka terjadi pembiaran. Pembiaran itu jadi awal dari boleh jadi orang-orang terbiasa untuk mengakses tanpa verifikasi,” ujarnya.
Sementara, Megandika menyampaikan gagasan kekerasan simbolik dari filsuf yang juga sosiolog Prancis Pierre Bourdieu (1930-2002) dalam media sosial. Kekerasan simbolik dalam pandangan Bourdieu adalah kekerasan yang sulit dideteksi, tidak ada unsur destruksi atau merusak secara fisik yang tampak langsung. Selain itu, kekerasan jenis ini beroperasi di bawah ketidaksadaran pelaku maupun korbannya sehingga bersifat nirsadar dan laten. “Apa yang menjadi trending di media sosial seolah memaksa orang untuk menirunya atau minimal mengomentarinya. Dampaknya secara psikologi, orang akan mencintai atau justru sebaliknya malah membenci,” tutur Megandika.
Dr. Edi Santoso menggarisbawahi bahwa berdasarkan riset dari Microsoft yang menyebutkan netizen Indonesia sebagai yang paling tidak sopan berarti menunujukkan bahwa netizen +62 paling sering melakukan kekerasan simbolik. “Media sosial tidak bisa dipungkiri jadi ruang interaksi. Dalam interaksi itu, kita temukan banak fenomena: anarkisme, narisisme, dan kekerasan simbolik yang bisa memakan korban. Orang yang melakukan impresi kalau berlebihan maka akan capek. Jadi tantangan bagaimana kita mengelola diri kita dengan yang lain,” ujarnya.
Diskusi yang diikuti sekitar 40 orang dari berbagai tempat secara virtual itu dimulai sejak pukul 19.15 dan selesai sekitar pukul 21.00. Para pemantik dan peserta diskusi tampak antusias dari sejumlah pertanyaan yang disampaikan. Topik bahasan diskusi online ini dinilai renyah karena dekat dengan keseharian dan dinamis. Mari sama-sama bijak bermedia sosial. (Megandika)